Pendahuluan: Manusia Digital yang Semakin Sendiri
Teknologi seharusnya mendekatkan manusia, tapi justru dalam banyak hal membuat kita semakin jauh secara sosial.
Kehidupan modern yang dikelilingi smartphone, media sosial, dan dunia digital membentuk gaya hidup baru: terhubung secara online, terpisah secara emosional.
Fenomena ini menggambarkan individualisme digital, di mana hubungan sosial bergeser dari interaksi langsung menjadi sekadar koneksi virtual.
Menurut Prof. Paulus Wirutomo, sosiolog Universitas Indonesia, “era teknologi menciptakan paradoks sosial — semakin banyak koneksi, semakin sedikit interaksi bermakna.”
Individualisme dalam Perspektif Sosiologis
Individualisme secara klasik didefinisikan oleh Émile Durkheim sebagai kecenderungan manusia modern untuk lebih menonjolkan kepentingan pribadi daripada solidaritas sosial.
Dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial didasarkan pada kebersamaan (mechanical solidarity).
Namun, dalam masyarakat modern dan digital, hubungan sosial bersifat kontraktual dan fungsional (organic solidarity).
Fenomena ini kini berkembang menjadi individualisme digital, di mana identitas dan relasi manusia dibangun melalui media sosial, bukan komunitas nyata.
Dr. Imam B. Prasodjo (UI) menilai bahwa “teknologi menciptakan ilusi kebersamaan yang justru memperkuat kesendirian eksistensial.”
Media Sosial dan Munculnya Budaya “Aku”
Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) membentuk budaya baru: budaya narsistik dan performatif.
Manusia tidak hanya hidup, tapi juga “memamerkan kehidupan.”
Fenomena ini disebut self-branding culture, di mana nilai sosial diukur dari jumlah likes, views, atau followers.
Menurut Pusat Kajian Komunikasi UI (2024), 71% pengguna muda di Indonesia merasa cemas jika tidak mendapat interaksi digital selama 24 jam.
Artinya, validasi sosial kini tidak lagi berasal dari komunitas nyata, tapi dari ruang maya.
Media sosial juga menciptakan filter bubble, yaitu ruang digital yang menampilkan konten sesuai minat pengguna, membuat mereka terjebak dalam gelembung pandangan pribadi.
Hasilnya? Semakin sedikit perbedaan pandangan yang diterima, semakin tinggi ego individual.
Teknologi dan Isolasi Sosial
Kemajuan teknologi komunikasi seolah memberi ruang tak terbatas untuk berinteraksi.
Namun, di balik layar, banyak individu merasa terisolasi secara sosial.
Penelitian BRIN (2024) menunjukkan bahwa penggunaan gawai lebih dari 6 jam per hari berkorelasi dengan meningkatnya rasa kesepian pada usia 18–35 tahun.
Fenomena ini disebut technological loneliness — kesepian yang lahir dari keterhubungan digital berlebihan.
Kita tidak lagi berbagi waktu dan emosi secara langsung, melainkan melalui emoji dan teks singkat.
Dr. Devi Asmarani (pengamat sosial Universitas Indonesia) menilai bahwa “hubungan sosial yang dibangun lewat layar tidak bisa menggantikan interaksi fisik yang melibatkan empati.”
Hal ini menjelaskan mengapa banyak anak muda mengalami burnout sosial meski aktif di dunia digital.
Perubahan Nilai Sosial di Era Teknologi
Arus teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mengubah nilai sosial dan makna kebersamaan.
Dalam masyarakat modern, muncul nilai-nilai baru seperti efisiensi, kecepatan, dan kompetisi, yang menggantikan nilai solidaritas dan gotong royong.
Riset LIPI (2023) menyebut bahwa masyarakat perkotaan kini lebih fokus pada pencapaian individu dibanding kontribusi sosial.
Hal ini terlihat dalam pola kerja jarak jauh (remote working), gaya hidup self-care, dan meningkatnya ketergantungan pada layanan digital yang bersifat personal.
Akibatnya, ikatan sosial melemah.
Hubungan sosial berubah menjadi transaksi emosional — mengikuti algoritma, bukan keintiman.
Banyak orang kini punya jaringan luas tapi hubungan dangkal.
Dampak Individualisme terhadap Struktur Sosial
Individualisme digital memiliki beberapa dampak sosial signifikan:
- Menurunnya Kohesi Sosial
Ikatan antarwarga melemah karena interaksi lebih banyak terjadi di dunia maya. - Meningkatnya Kompetisi Sosial
Masyarakat terjebak dalam budaya perbandingan sosial (social comparison culture) yang memicu stres dan ketidakpuasan diri. - Polarisasi dan Empati Rendah
Algoritma digital mendorong kita hanya berinteraksi dengan kelompok sependapat, memperkuat intoleransi sosial. - Krisis Identitas Sosial
Individu lebih sibuk membangun citra digital daripada memahami jati diri sosialnya.
Menurut Prof. Melani Budianta (UI), “identitas sosial di era digital bukan lagi refleksi jati diri, melainkan hasil konstruksi algoritma dan ekspektasi sosial.”
Tantangan Sosial dan Jalan Keluar
Fenomena individualisme digital tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan melalui kesadaran sosial dan pendidikan digital yang lebih humanis.
Beberapa strategi yang bisa dilakukan:
- Membangun Literasi Digital Humanistik
Pendidikan teknologi harus menekankan aspek empati, etika, dan tanggung jawab sosial. - Mendorong Komunitas Sosial Nyata
Ruang-ruang komunitas fisik seperti kampus, organisasi sosial, dan kegiatan masyarakat perlu dihidupkan kembali. - Mendesain Teknologi yang Inklusif
Platform digital seharusnya tidak hanya mengejar interaksi, tapi juga mendorong dialog dan keberagaman pandangan. - Menumbuhkan Spirit Gotong Royong Digital
Kolaborasi online bisa menjadi sarana memperkuat solidaritas jika diarahkan untuk tujuan sosial, bukan hanya personal branding.
Sebagaimana dikatakan Dr. Imam Prasodjo, “teknologi harus menjadi alat memperluas kemanusiaan, bukan menipiskan rasa kemanusiaan.”
Kesimpulan: Mengembalikan Manusia di Tengah Teknologi
Individualisme di era teknologi adalah konsekuensi dari modernitas — tapi bukan akhir dari solidaritas.
Manusia tetap memiliki kapasitas sosial untuk beradaptasi dan membangun kembali empati melalui media baru.
Kuncinya ada pada kesadaran: bahwa teknologi hanyalah alat, bukan pengganti relasi manusia.
Demokrasi sosial digital harus dibangun atas dasar nilai gotong royong, empati, dan interaksi yang bermakna.
Seperti pesan Prof. Paulus Wirutomo, “masa depan masyarakat digital bukan tentang seberapa cepat kita terhubung, tapi seberapa dalam kita saling memahami.”
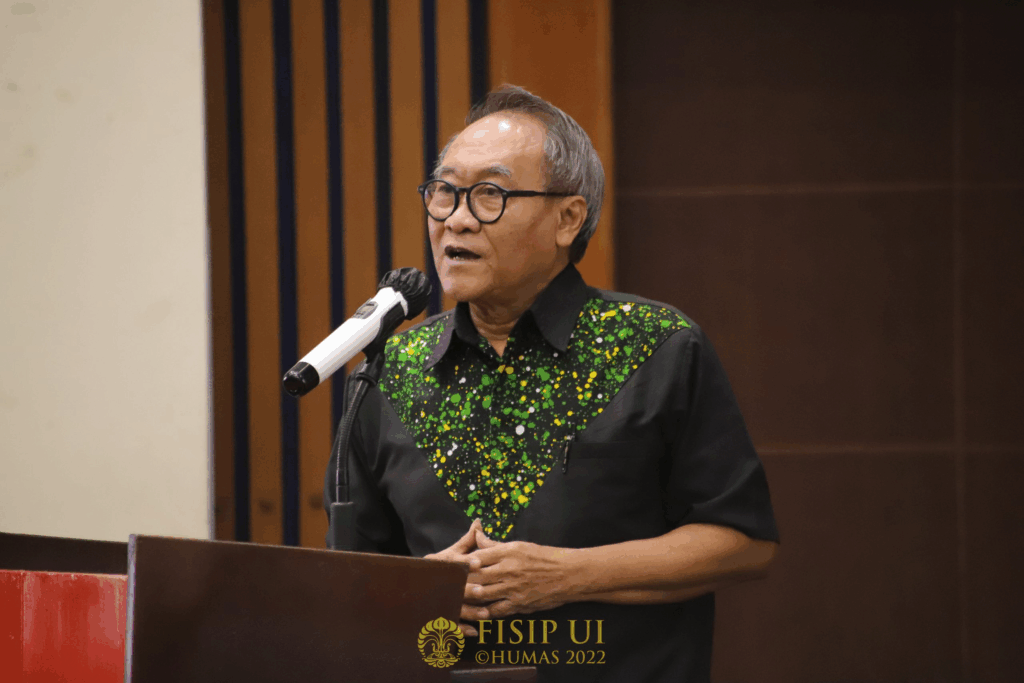
Sumber & Referensi:
- Prof. Paulus Wirutomo (UI), Sosiologi Digital dan Perubahan Sosial (2024)
- Dr. Imam B. Prasodjo (UI), Manusia Modern dan Krisis Solidaritas Sosial (2023)
- BRIN, Teknologi dan Kesepian Sosial di Indonesia (2024)
- LIPI, Transformasi Nilai Sosial di Masyarakat Perkotaan (2023)
- Pusat Kajian Komunikasi UI, Digital Lifestyle and Social Behavior (2024)
- SAFEnet, Digital Culture and Human Connection Report (2024)

