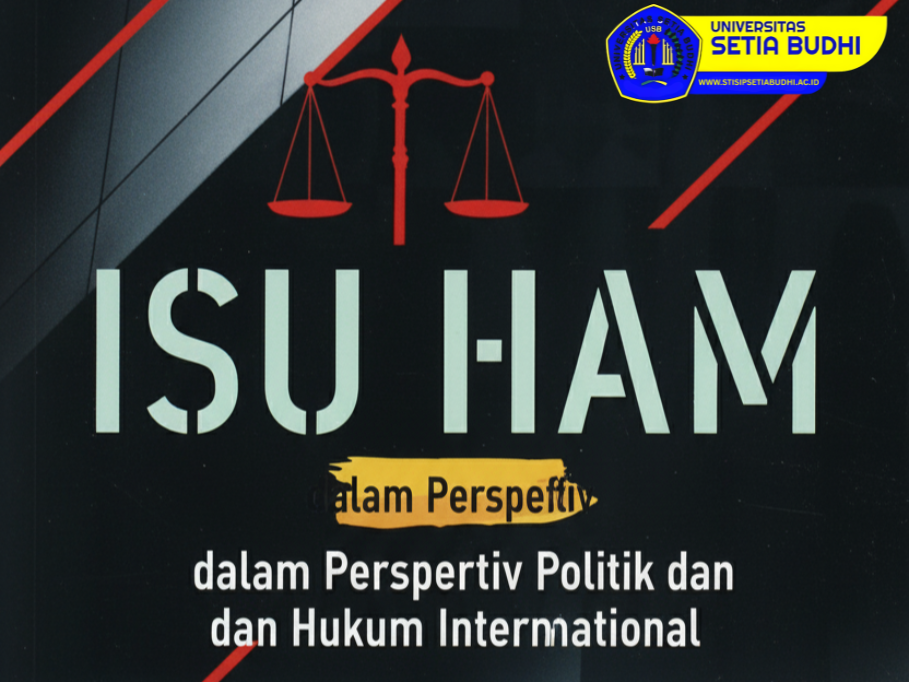Pendahuluan: HAM di Persimpangan Politik Global
Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu isu paling krusial dalam hubungan internasional modern.
Dari genosida di masa lalu hingga kebijakan imigrasi dan kebebasan berekspresi di era digital, HAM selalu menjadi topik yang menuntut keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban moral universal.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, “HAM tidak bisa dilepaskan dari politik kekuasaan. Siapa yang memiliki pengaruh global, dia yang menentukan arah wacana HAM.”
Pernyataan ini menggambarkan bagaimana isu HAM kerap digunakan sebagai alat diplomasi, bahkan tekanan politik antarnegara.
Latar Historis: Dari Deklarasi Universal hingga Mekanisme Internasional
Konsep HAM secara formal diakui pasca Perang Dunia II, ketika dunia menyaksikan dampak mengerikan dari kekerasan negara terhadap warganya.
Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menjadi dasar bagi hukum HAM internasional modern.
Sejak saat itu, muncul berbagai konvensi internasional seperti:
- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
- ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
- CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
Ketiga instrumen ini menjadi kerangka hukum yang mengikat negara-negara anggota untuk melindungi hak-hak warga negaranya.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua negara menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten.
Sebagian negara, terutama di dunia berkembang, menghadapi dilema antara menegakkan HAM dan mempertahankan stabilitas politik dalam negeri.
HAM dalam Perspektif Politik Internasional
Dalam tataran politik global, isu HAM sering kali digunakan sebagai instrumen kekuasaan dan diplomasi.
Negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerap menjadikan isu HAM sebagai syarat dalam hubungan ekonomi dan bantuan internasional.
Dr. Dewi Fortuna Anwar (BRIN) menjelaskan bahwa “politik HAM global cenderung bersifat selektif. Negara besar menyoroti pelanggaran HAM di negara lain, tapi menutup mata terhadap sekutunya sendiri.”
Hal ini terlihat misalnya dalam perbedaan respons internasional terhadap konflik Palestina dan Ukraina — dua tragedi kemanusiaan yang mendapat perhatian tidak seimbang.
Selain itu, organisasi internasional seperti PBB dan Dewan HAM (UNHRC) memiliki keterbatasan karena keputusan mereka bersifat non-binding (tidak mengikat secara hukum).
Artinya, efektivitas penegakan HAM global masih sangat tergantung pada kemauan politik masing-masing negara.
HAM dalam Perspektif Hukum Internasional
Secara hukum, perlindungan HAM diatur melalui instrumen internasional yang mengikat negara-negara penandatangan.
Namun, pelaksanaannya tidak sederhana karena adanya prinsip kedaulatan negara (state sovereignty).
Dalam sistem hukum internasional, tidak ada otoritas tertinggi yang bisa memaksa negara menjalankan kewajibannya, kecuali melalui mekanisme tribunal internasional, seperti:
- International Criminal Court (ICC) untuk kasus genosida dan kejahatan perang,
- International Court of Justice (ICJ) untuk sengketa antarnegara,
- Human Rights Council untuk evaluasi periodik negara melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR).
Dr. Marzuki Darusman, mantan Ketua Komisi HAM PBB untuk Korea Utara, menegaskan, “hukum HAM internasional baru efektif jika negara bersedia membuka diri terhadap pengawasan global. Tanpa transparansi politik, instrumen hukum hanya tinggal dokumen.”
Posisi Indonesia dalam Isu HAM Global
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam isu HAM global.
Indonesia telah meratifikasi sebagian besar instrumen HAM internasional dan membentuk lembaga nasional seperti Komnas HAM serta Komnas Perempuan.
Namun, tantangan tetap ada. Kasus-kasus seperti pelanggaran HAM berat masa lalu (Timor Timur, 1965, Papua) masih menjadi sorotan internasional.
Menurut laporan Human Rights Watch (2024), penyelesaian yudisial terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia masih berjalan lambat dan sering kali berhenti di tahap politik.
Meski demikian, Indonesia tetap aktif dalam diplomasi HAM di kawasan ASEAN.
Melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Indonesia mendorong penguatan norma HAM di tingkat regional, meski efektivitasnya masih terbatas.
Tantangan Politik HAM di Era Digital
Era digital membawa bentuk baru pelanggaran HAM, seperti penyalahgunaan data pribadi, ujaran kebencian, dan disinformasi.
Kominfo (2024) mencatat lebih dari 12.000 kasus penyebaran kebencian daring di Indonesia sepanjang tahun lalu, yang banyak terkait isu ras, agama, dan politik.
Dr. Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM, menyebut bahwa “perlindungan HAM di era digital harus memperluas makna privasi dan kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial.”
Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional harus terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika politik global.
Kritik terhadap Standar Ganda HAM Global
Salah satu kritik utama terhadap rezim HAM internasional adalah standar ganda (double standards).
Negara besar kerap menggunakan isu HAM sebagai alat politik luar negeri, bukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan.
Contohnya, sanksi ekonomi terhadap negara tertentu sering justru memperburuk kondisi warga sipil, bukan memperbaiki pelanggaran HAM.
Kritik ini disuarakan pula oleh Amnesty International dan South Centre (2023), yang menilai bahwa pendekatan HAM global masih terlalu berpusat pada kepentingan geopolitik negara maju.
Karena itu, banyak negara berkembang — termasuk Indonesia — mendorong model “dialog HAM konstruktif”, bukan konfrontatif, agar isu HAM tidak digunakan sebagai alat tekanan politik.
Menuju Penegakan HAM yang Adil dan Universal
Untuk memperkuat penegakan HAM, dibutuhkan sinergi antara hukum internasional, diplomasi, dan kesadaran politik nasional.
Ada tiga langkah penting:
- Memperkuat Komitmen Domestik
Negara harus memperkuat lembaga hukum dan memastikan bahwa pelanggaran HAM diusut secara transparan. - Reformasi Mekanisme Global
PBB perlu meningkatkan efektivitas Dewan HAM dan memperluas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional agar lebih inklusif. - Pendidikan HAM dan Literasi Kewargaan
Kesadaran HAM tidak cukup melalui hukum, tapi juga pendidikan publik dan peran media independen.
Sebagaimana diingatkan oleh Nelson Mandela, “Kebebasan sejati bukan sekadar terbebas dari rantai, tapi hidup dalam cara yang menghormati kebebasan orang lain.”
Kesimpulan: HAM antara Idealitas dan Realitas Politik
Isu HAM selalu berada di antara dua kepentingan: keadilan moral universal dan realitas politik nasional.
Dalam konteks internasional, hukum HAM tidak bisa berjalan tanpa komitmen politik negara-negara pelaksana.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi jembatan antara dunia maju dan berkembang dalam memperjuangkan HAM yang kontekstual dan adil.
Sebagaimana dikatakan Prof. Hikmahanto Juwana, “masa depan HAM global bergantung pada keberanian negara-negara untuk menegakkan nilai kemanusiaan tanpa selektivitas politik.”
HAM bukan hanya wacana hukum, tapi cerminan peradaban — sejauh mana manusia menghargai martabat sesamanya.

Sumber & Referensi:
- Prof. Hikmahanto Juwana (UI), Politik Hukum Internasional dan HAM Global (2023)
- Dr. Marzuki Darusman, United Nations Human Rights Reports (2023)
- Dewi Fortuna Anwar (BRIN), Isu HAM dan Diplomasi Indonesia (2024)
- Human Rights Watch, World Report 2024 – Indonesia Chapter
- Amnesty International, Global Human Rights Review (2023)
- Kominfo, Laporan Perlindungan Data dan Kebebasan Digital (2024)